Kajian New Historicism Pada Novel Laut Bercerita Karya Laela S. Chudori
Bangsa Indonesia tidak mungkin terlepas dari sejarah yang terjadi di masa lalu. baik yang terdokumentasi dalam buku-buku sejarah maupun yang tidak. Dalam konteks sejarah tersebut, terdapat beberapa sastrawan yang menjadikan peristiwa sejarah menjadi karya sastra. Rupanya, antara sejarah dengan karya sastra saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Pernyataan tersebut, sesuai dengan pendapat Wellek dan Warren (via Sahliyah, 2017: 109) jika suatu karya sastra dapat dipandang sebagai rangkaian karya yang disusun berdasarkan urutan waktu dan merupakan bagian dari perjalanan sejarah. Untuk itu, terciptanya karya sastra dipengaruhi oleh proses sejarah. Leila S. Chudori merupakan salah satu sastrawan yang menggambarkan peristiwa sejarah dalam novelnya yang berjudul Laut Bercerita.
Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori dikaji dengan pendekatan New Historicism. Kajian ini lebih menekankan hubungan antara teks sastra dan teks non-sastra. Pendekatan ini melibatkan analisis sejarah yang mencakup kajian sejajar antara teks sastra dan non-sastra. Ardhianti (2016:3) menjelaskan awal munculnya New Historicism yang tidak dapat dilepaskan dari kajian sastra dan ilmu pengetahuan lainnya. Semenjak Perang Dunia II, kajian sastra menjadi disiplin yang istimewa. Terdapat bahasan mengenai berbagai karya sastra dari aspek keindahan, struktur kebahasaan dan pesan-pesan tekstual yang terkandung di dalamnya. Kemudian pada tahun 1960-an muncul keinginan diantara para profesor sastra Eropa untuk menjadikan disiplin sastra memiliki peran dalam memahami dan memecahkan problem sosial aktual. Dalam hal ini, karya sastra perlu dilihat tidak hanya sekadar dari aspek estetika, tetapi sebagai produk budaya dari jamannya.
Kerangka berpikir yang berubah dalam memandang karya sastra memunculkan gerakan “kembali ke sejarah” dalam arti mengkaji historisitas dari teks karya sastra dan tektualitas karya sejarah. Gerakan “kembali ke sejarah” yang dimunculkan para ahli sastra di Eropa dapat dikatakan telah mencapai kematangan karena berkembang meluas ke Inggris dan Amerika Serikat dalam taraf tertentu. Greenblatt mengenalkan istilah New Historicism pada awal tahun 1980-an dalam kajian-kajiannya tentang puisi kultural. Greenblatt menghancurkan kecenderungan kajian tekstual-formalis dalam tradisi New Historicism yang dipandangnya bersifat ahistoris. Greenblatt juga memandang sastra sebagai sebuah wilayah estetik yang berdiri sendiri dan dipisahkan dari aspek-aspek yang dianggap berada di luar karya tersebut (Brannigan via Ardhianti, 2016:3).
Pada tahun 1982 Stephen Greenblatt dalam sebuah pengantar edisi jurnal Genre menggunakan istilah New Historicism untuk menawarkan perspektif baru dalam kajian renaissance. Hal ini dilakukan untuk menekankan keterkaitan teks sastra dengan berbagai kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupinya (Artika, 2015:51).
New Historicism bukanlah ajaran mengenai asas suatu aliran politik atau keagamaan, tetapi lebih merupakan model kerja. Sederhananya New Historicism merupakan metode penelitian mengenai masa lampau berdasar penempatan dokumen historis dan nonhistoris seperti karya sastra, antara sumber tertulis dengan nontertulis seperti gambar atau anekdot sebagai sumber yang penting (Ardhianti, 2016:3). New Historicism lebih dikenal sebagai bagian dari kajian budaya karena kajian yang dilakukan lintas disiplin.
Artika (2015:51) menyebutkan jika New Historicism mengandung dua hal, yaitu mengerti sastra melalui sejarah dan mengetahui budaya, sejarah, dan pemikiran melalui sastra. Dalam hal ini, New Historicism tidak membedakan teks sastra dengan nonsastra, seperti pandangan old history yang memandang sejarah sebagai latar belakang karya sastra atau new criticism berupa sastra otonom atau ahistory.
Ryan (2011:217) menjelaskan jika New Historicism merupakan sastra dalam kerangka hubungan dengan teks nonsastra, karena argumen mengenai makna teks sastra sering sekali mudah diuraikan dengan melihat sejarah. Sejarah itu bagaikan pisau analisis yang kuat karena seringkali memberikan dasar yang kokoh untuk memancangkan pernyataan yang berhubungan dengan makna.
Myers (vieArdhianti, 2016:4) meyebutkan empat asumsi New Historicism, sebagai berikut.
a. Karya sastra bernilai sejarah, bukan sekadar catatan tentang pikiran seseorang. Untuk memahami karya sastra harus dikaitkan dengan sosio budaya yang menghasilkannya.
b. Karya sastra merupakan pandangan tertentu terhadap sejarah.
c. Seperti halnya karya sastra, manusia, termasuk ahli sejarah dan kritikus juga mengalami bentuk tekanan sosial politik.
d. Akibatnya ahli sejarah atau kritikus sastra terjebak pada kesejarahannya sendiri. Tak seorangpun yang mampu bangkit dari strukur sosialnya sendiri.
New Historicism memiliki prinsip bahwa tidak ada sejarah yang objektif, padu, dan cermat (Ardhianti, 2016:5). Semua sejarah merupakan hasil tulisan orang dan akan selalu bisa ditulis ulang. New Historicism tidak hanya membaca peristiwa sebagai urutan ruang dan waktu secara lurus. Peristiwa tersebut dibaca dan dipahami sebagai kejadian yang saling berhubungan dan saling tergantung sebagai peristiwa yang tidak terjadi begitu saja. Dibalik peristiwa atau kejadian historis itu harus dicurigai banyak hal yang melatarbelakangi.
Kejadian historis tidak cukup logis jika hanya dikatakan sebagai sesuatu yang kebetulan. Kejadian historis tersebut dicurigai terdapat persoalan-persoalan mendasar yang melatarinya seperti persolan ideologi, politik, dan sosio-kultural. Dalam hal ini, menurut teori New Historicsm tugas yang utama dalam melihat fenomena atas peristiwa historis ialah membongkar dimensi ideologi, politik, dan sosio-kultural (Ardhianti, 2016:5). Di saat yang sama, membuka daya operasi yang bergerak di dalamnya. Dengan demikian, kerja utama New Historicism yakni membaca, membongkar, dan menelaah kembali peristiwa sejarah dalam konteks ideologi, politik, dan sosio-kultural.
Berdasarkan pendapat yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli di atas, New Historicism tidak memberikan perlakuan khusus kepada teks sastra, tetapi memberikan perlakuan yang setara terhadap teks nonsastra. Kajian ini akan meneliti aspek sejarah yang terdapat dalam novel, lalu membandingkannya dengan teks sejarah yang mengandung fakta-fakta yang sama seperti yang ada dalam novel tersebut. Sumber-sumber teks nonsastra yang akan digunakan sebagai perbandingan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori ini berasal dari berbagai sumber, seperti teks sejarah, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya untuk mengkaji novel ini.
Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori berlatarkan peristiwa sejarah Orde Baru. Mengisahkan peristiwa besar di dalam sejarah Indonesia terkait perilaku kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh kelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Salah satu aktivis mahasiswa bernama Biru Laut, dalam upayanya bersama rekan-rekan sesama mahasiswa menggulingkan kediktatoran pemerintahan yang berkuasa lebih dari 3 dekade pada saat itu di Indonesia. Pembahasan yang dikaji tidak hanya masalah sejarah pada masa orde baru, melainkan masalah budaya dan ekonomi.
KAJIAN NEW HISTORICISM PADA NOVEL LAUT BERCERITA KARYA LAELA S. CHUDORI
Representasi Sejarah Indonesia Dalam Novel Laut Bercerita
Persoalan yang dialami tokoh utama dalam novel Laut Bercerita dipicu oleh peristiwa sejarah yang muncul dalam novel tersebut. Peristiwa sejarah tersebut menjadikan alur kehidupan tokoh dapat terlihat dalam peristiwa sejarah tersebut. Penggambaran sejarah dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori berfungsi untuk menghidupkan kembali tragedi sejarah masa pemerintahan Orde Baru yang terdapat dalam teks-teks cerita pada novel tersebut.
Representasi sejarah dalam novel Laut Bercerita mengarah pada kepemimpinan otoriter yang didominasi oleh kekuatan militer. Pada masa kepemimpinan Soeharto militer digunakan dalam menekan luapan massa. Apabila massa dicurigai mengganggu keamanan negara maka militer akan bertindak dengan cekatan. Peristiwa kekuasaan negara dengan kekuatan militer pada masa Orde Baru dalam novel Laut Bercerita terdapat pada kutipan berikut.
Mereka pasti memiliki lemari es gigantik karena gemar sekali membangunkan kami dengan seember es. Terdengar Daniel berteriak dan menyumpah-nyumpah. Alex terdengar menggeram-geram, sedangkan aku masih mencoba berdamai dengan setumpuk darah kering pada bibir, wajah bengkak, dan tulang hidung yang patah, yang membuatku sulit bernapas. Aku hanya bisa berharap kepala dan sebagian badanku yang basah oleh siraman es ini akan kering dengan sendirinya karena kedua tanganku masih diikat ke pojok velbed. Salah seorang dari mereka mendekatiku. Aku bisa merasakan tangan sebesar kayu balok itu mencengkeram pergelangan tanganku (Chudori, 2017:92).
Kutipan di atas menunjukkan kekuatan militer digunakan untuk mengatasi gejolak masyarakat jika massa rusuh, maka tentara diturunkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tak pandang bulu, orang-orang yang dicurigai membuat keributan dan mengguncang keamanan negara segara ditangkap, diinterogasi, bahkan disiksa. Tidak hanya keras dan kejam, sosok militer juga memiliki strategi yang baik dalam mengamankan negara.
Kekuatan intel yang sigap menyelidiki permasalahan di masyarakat dengan menyamar sebagai bagian dari masyarakat, dapat mencegah segala kegaduhan massa. Dengan demikian, desas-desus dimasyarakat yang ingin memberontak dapat segera diketahui dan diatasi. Pengungkapan Leila S. Chudori mengenai otoritas pemerintah Orde Baru sebagai rezim dengan kekuatan militer yang kuat juga sesuai dengan pendapat Wiratraman (2014:274) yang menyatakan bahwa Pada era Orde Baru, pemerintah mengendalikan media dengan menggunakan berbagai taktik seperti pengaturan perizinan, pelarangan, serta penangkapan terhadap jurnalis atau editor yang menyampaikan pendapat yang kontra atau menentang kebijakan pemerintah.
Representasi Budaya Dalam Novel Laut Bercerita
Budaya yang tergambarkan dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori merujuk pada bagaimana budaya Indonesia tertulis dalam novel. Budaya yang tercermin dalam novel Laut Bercerita mencakup aspek budaya dari bangsa Indonesia, yaitu budaya Jawa. Aspek budaya tersebut meliputi penggunaan bahasa Jawa. Penggunaan bahasa Jawa dalam novel Laut Bercerita terlihat dalam kutipan berikut.
"Senenge pancen ditandangi dhewe." kata Mas Yunus (Chudori, 2017:18).
“Lha…awakmu piye, Laut?” (Chudori, 2017:144)
Terdapat penggunaan bahasa Jawa dalam novel Laut Bercerita yang dapat dilihat dari kutipan di atas. Penggunaan bahasa Jawa dalam lingkup masyarakat Jawa menjadi salah satu aspek kebudayaan Jawa (Sahliyah, 2017:113). Kebudayaan Jawa tersebut merupakan aspek budaya yang termasuk satu konsep dari New Historicism, hal ini sesuai dengan pendapat Budianta (2006:8) jika budaya menjadi unsur yang tak terpisahkan dalam karya sastra, dengan kehadirannya yang secara tidak langsung memberikan sentuhan khusus pada karya tersebut. Lebih dari sekadar pelengkap, budaya mampu memberikan daya tarik yang membuat karya sastra menjadi lebih menarik untuk dinikmati.
Representasi Ekonomi Dalam Novel Laut Bercerita
Penggambaran ekonomi dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori ini akan mengarah pada bagaimana ekonomi bangsa Indonesia yang digambarkan oleh pengarang ke dalam novel. Keadaan ekonomi dalam novel Laut Bercerita digambarkan dalam tragedi sebelum tahun 1998, terjadi penurunan ekonomi yang salah satu faktornya adalah tingginya tingkat inflasi yang tidak dapat dihindari. Representasi kemiskinan sebelum tragedi 1998 terdapat dalam kutipan berikut.
Sambil duduk di sebelahnya, melihat sinar mesin fotokopi itu sesekali memberi nyala pada wajahnya, kami berbincang seperti kawan lama. Sama seperti aku, Kinan juga lahir dan besar di Solo. Bapaknya, Bambang Prasojo adalah pegawai pegadaian yang setiap bulan Juni harus menghadapi para orangtua yang menggadaikan barang-barangnya karena itulah bulan-bulan gawat orangtua menghadapi gerogotan tahun ajaran baru sekolah: seragam, buku, dan alat tulis. "Dari sepeda motor hingga panci pressure cooker," kata Kinan sambil membereskan semua fotokopinya yang sudah selesai (Chudori, 2017:18).
Pada kutipan tersebut terdapat penggambaran terjadinya inflasi yang merupakan salah satu indikasi kemiskinan pada era Orde Baru sebelum tragedi tahun 1998. Dalam kondisi inflasi tersebut, terjadi situasi di mana banyak barang yang digadaikan di kantor pegadaian tidak dapat diambil kembali oleh pemiliknya karena kekurangan uang pada saat tahun ajaran baru sekolah. Tidak hanya itu saja, masyarakat kecil juga terpaksa meminjam uang kepada rentenir karena tekanan ekonomi yang mereka hadapi. Dalam beberapa kasus, seseorang yang tidak mampu membayar utang mengalami stres yang parah atau bahkan melakukan tindakan bunuh diri.
Inflasi mengakibatkan harga barang-barang melambung tinggi sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat. Hal ini menggambarkan kemiskinan yang berkecamuk. Kondisi ekonomi masyarakat yang rendah menandakan kurang tercukupinya kebutuhan masyarakat. Peristiwa inflasi ini telah dijelaskan oleh Biro Analisa dan Pelaksanaan APBN (2019:27) jika Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar 77,63% dan inflasi terendah pada tahun 1999 sebesar 2,01%.
PENUTUP
Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (a) representasi sejarah Indonesia dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori mengenai peristiwa pada masa Orde Baru dimana peristiwa sejarah tersebut berupa kekuasaan negara dengan kepemimpinan yang didukung oleh kekuatan militer secara otoriter dan represif. Kepemimpinan itu ditunjukkan melalui kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Terdapat pula pertarungan kekuasaan yang memicu gerakan mahasiswa; (b) representasi budaya dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori, yaitu budaya Jawa yang meliputi penggunaan bahasa Jawa; (c) representasi ekonomi yang digambarkan dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori merupakan suatu kondisi perekonomian yang lemah hingga mengakibatkan inflasi di mana harga kebutuhan pokok naik, rakyat bergantung pada pegadaian dan rentenir, bahkan dalam beberapa kasus seseorang yang tidak mampu membayar utang mengalami stres yang parah atau bahkan melakukan tindakan bunuh diri.
DAFTAR PUSTAKA
Ardhianti, Mimas. 2016. Kajian New Historicism Novel Hatta: Aku Datang Karena Sejarah Karya Sergius Sutanto. Jurnal Buana Sastra. Volume 3, No 1. Diakses dari https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/bastra/article/download/652/519/1979
Artika, I Wayan. 2015. Pengajaran Sastra Dengan Teori New Historicism. Jurnal Prasi. Vol 10, No 2. Diakses dari https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/PRASI/article/download/8917/5756/0
Biro Analisa dan Pelaksanaan APBN. 2019. Analisis Keberadaan Tradeoff Inflasi Dan Pengangguran (Kurva Phillips) Di Indonesia. Doi: https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_analisis_keberadaan_tradeoff_inflasi_dan_pengangguran_%28kurva_phillips%29_di_indonesia20140821142142.pdf
Budianta, M. (2006). Budaya, Sejarah, dan Pasar: New Historicism Dalam Perkembangan Kritik Sastra. Jakarta: HISKI Yayasan Obor Indonesia.
Chudori, Leila S. 2017. Laut Bercerita. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Ryan, Michael. 2011. Teori Sastra, Sebuah Pengantar Praktis (Bethari Anissa Ismayasari penerjemah). Yogyakarta: Jalasutra.
Sahliyah, Chalifatus. 2017. Kajian New Historicism Pada Novel Kubah Karya Ahmad Tohari. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra. Vol. 17, No. 1. Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/118050-ID-kajian-new-historicism-novel-kubah-karya.pdf
Wiratraman, H.P. (2014). Kebebasan Pers, Hukum dan Politik di Indonesia: Sebuah Studi Sosial Hukum. Doi: https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-output/law/press-freedom-law-and-politics-in-indonesia
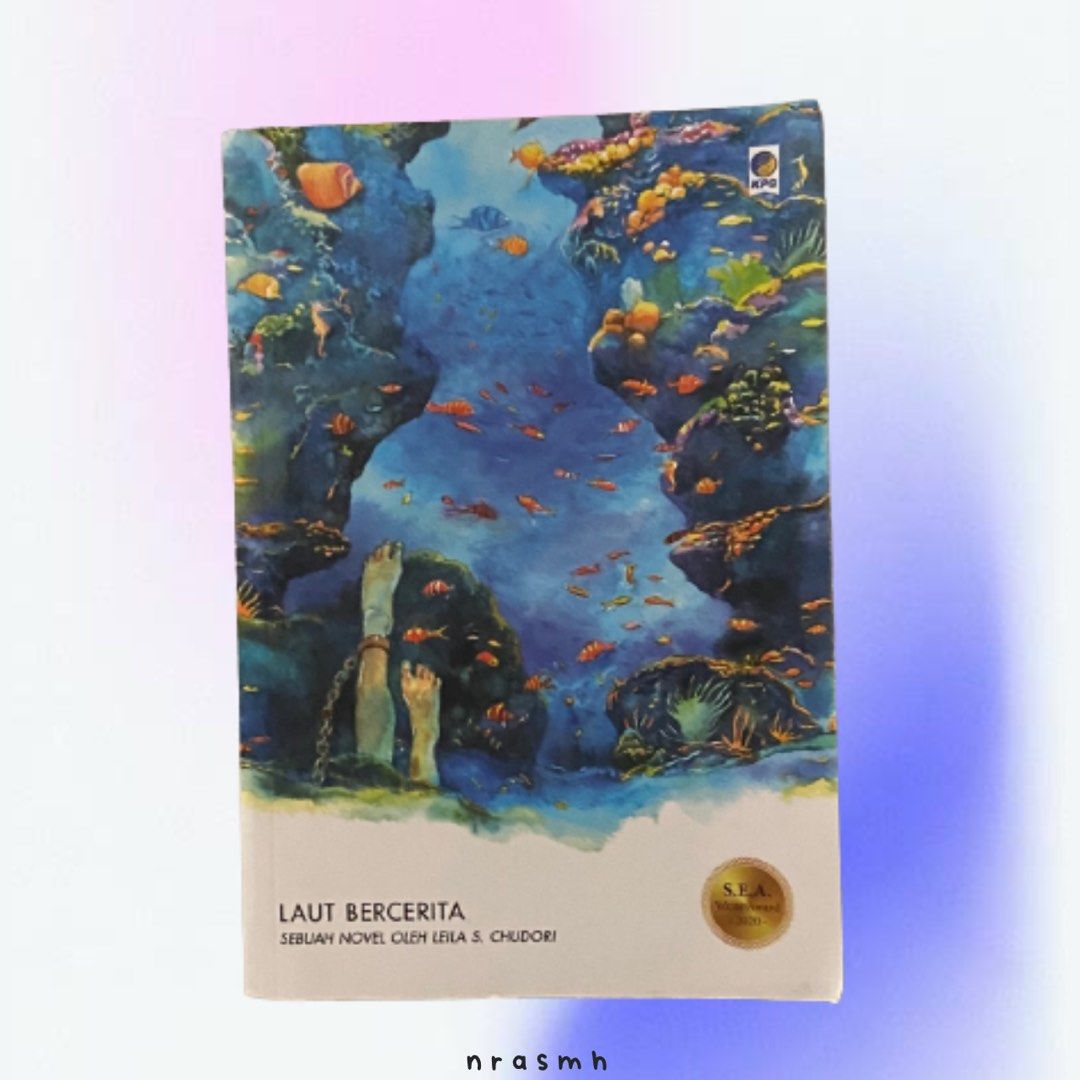
Komentar
Posting Komentar